Menelaah Hadis Shahih dengan Perbedaan Mazhab
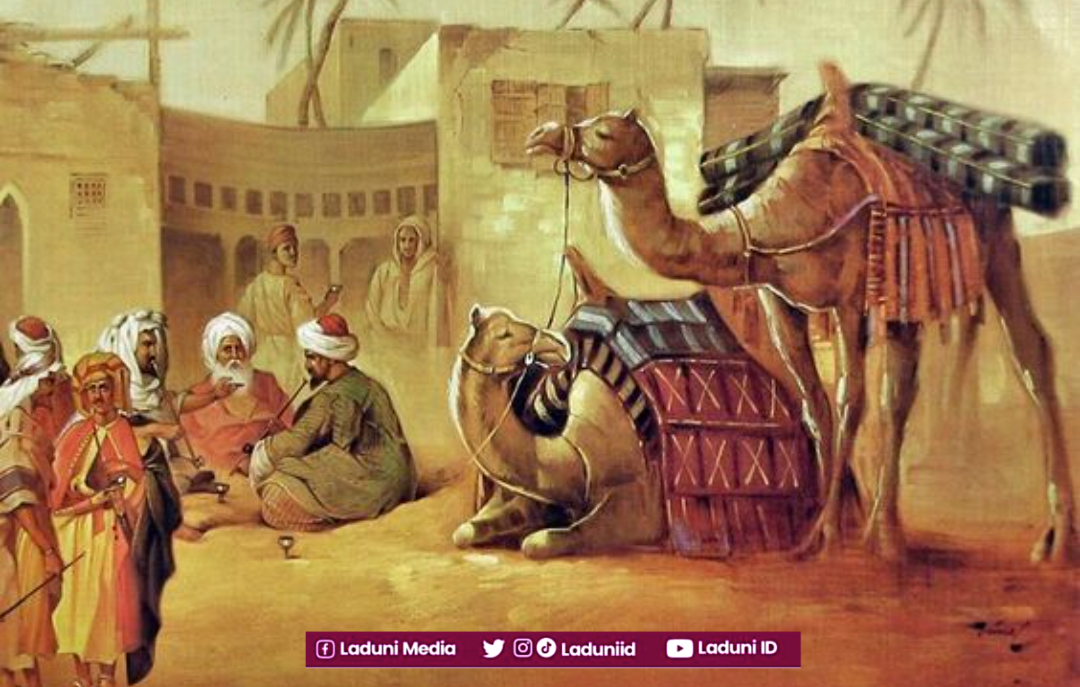
Laduni.ID, Jakarta - “Kenapa para ahli fikih itu tidak mau menjalankan isi Hadis yang nyata-nyata merupakan Hadis sahih?” begitu sering kita dengar sebagian kalangan berkata.
“Karena tidak semua Hadis sahih bisa langsung berlaku. Bisa jadi Hadis yang antum maksud itu ternyata dalam pandangan ahli fikih sudah di-mansukh oleh Hadis lainnya. Kalau kita luaskan bacaan kita lintas mazhab, insya Allah kita akan mendapati serunya diskusi para ulama klasik yang terekam dalam kitab kuning itu,” jawab saya dengan santai.
“Contohnya bagaimana?” tanya kawan tersebut yang masih penasaran.
“Ini contohnya, ada Hadis Sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim (Hadis nomor 360), bahwa setelah memakan daging unta Nabi Muhammad SAW menyuruh kita berwudhu kembali kalau hendak melaksanakan shalat. Ini mengindikasikan bahwa memakan daging unta adalah hal yang dapat membatalkan wudhu.”
“Maka, Mazhab Hambali menyatakan batalnya wudhu dengan memakan daging unta. Imam Ahmad, pendiri Mazhab Hambali ini selain ahli Hadis juga merupakan ahli fikih, dan beliau meriwayatkan Hadis senada mengenai keharusan berwudhu setelah mengonsumsi daging unta. Tetapi lebih serunya, beliau juga mencantumkan dalam kitabnya Musnad Ahmad (Hadis nomor 25094), bahwa Siti Aisyah menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW yang pernah makan daging unta dari panci di rumahnya dan dengan tanpa wudhu lagi nabi langsung shalat.”
Kontradiksi kah? Gak juga sih…
Inilah kejujuran ilmiah. Riwayat yang berbeda tetap dicantumkan dalam kitabnya, meskipun beliau sendiri berpegang pada Hadis lain yang berkebalikan dengan kisah Siti Aisyah.
Imam Syafi’i dalam qaul qadim-nya saat beliau di Baghdad juga berpendapat batalnya wudhu akibat makan daging unta. Namun saat beliau pindah ke Mesir, beliau mengubah pendapatnya dan bergabung bersama pendapat Mazhab Hanafi dan Maliki yang menyatakan bahwa wudhu tidak batal sebab makan daging unta. Bahkan diriwayatkan juga oleh Khulafa Ar-Rasyidin yang menerangkan bahwa mereka tidak mengulang berwudhu setelah makan daging unta.
Jadi lebih banyak ulama yang berpandangan bahwa memakan daging unta tidak membatalkan wudhu. Tapi dalam fikih, kebenaran itu tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah pendukung, sebagaimana postingan di media sosial yang tidak otomatis jadi benar gara-gara banyak yang klik like. Kebenaran ditentukan oleh kekuatan argumen dan dalil, bukan banyak-banyakan pengikut.
Ketiga mazhab di atas bukannya tidak menjalankan isi Hadis shahih, tapi mereka berpegang pada Hadis shahih lainnya (Sunan Abi Dawud, Hadis nomor 192 dan Sunan An-Nasa’i, Hadis nomor 185): “Tidak perlu berwudhu setelah makan makanan yang sudah di bakar api (dimasak).” Dari sini, sudah jelas kan? bahwa para ulama fikih tidak menafikan Hadis shahih. Mereka semua paham mengenai hal ini.
Tapi bukankah status Sahih Muslim lebih tinggi daripada Sunan Abi Dawud dan Sunan An-Nasa’i? Secara umum benar, tapi para ulama akan meneliti satu per satu Hadis tersebut dan tidak serta merta menganggap semua Hadis dalam Shahih Muslim itu lebih tinggi dibanding yang lain. Apalagi riwayat Abu Dawud itu didukung Hadis lainnya seperti; “Wudhu itu batal karena apa yang keluar bukan karena apa yang masuk.” Nah bagaimana kalau sudah begini? Masuk akal juga kan…?!
Ada juga ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud berwudhu dalam Hadis riwayat Muslim itu adalah makna harfiahnya, yaitu cuci tangan dan mulut setelah makan daging unta, bukan berwudhu dalam makna ritual. Nah, sampai di sini diskusi makin seru, karena apa yang dimaksud dalam sebuah Hadis pun bisa dipahami berbeda-beda termasuk dari aspek kebahasaan.
Imam Nawawi salah seorang ulama besar dalam Mazhab Syafi’i punya pendapat yang berbeda dengan qaul jadid-nya Imam Syafi’i. Dalam Syarh Shahih Muslim, beliau berpandangan bahwa yang lebih kuat itu adalah harus berwudhu setelah makan daging unta. Karena kalau alasannya Hadis riwayat Muslim telah di-mansukh oleh Hadis Abu Dawud, maka itu bertentangan dengan kaidah karena tidak bisa dalil ‘am menghapus ketentuan dalil khas.
Nah, kita lihat di sini Imam Nawawi sudah mulai berargumen dengan kaidah fikih, dan tidak lagi berpatokan pada status atau kekuatan Hadis. Itulah sebabnya membaca kitab Hadis saja tidak cukup untuk kita ber-istinbath, kita juga harus paham kaidah fikih dan kaidah ushul. Seru sekali kan diskusi para ulama klasik itu? Lebih seru lagi, bahwa Imam Nawawi tidak sungkan dalam berbeda pandangan dengan pendiri mazhabnya. Jadi, siapa bilang ulama mazhab itu kolot dan ngotot hanya berpatokan pada mazhabnya semata?
Tapi kalau mau dipikir lebih lanjut: Kenapa daging unta berbeda dengan daging kambing? Kenapa makan daging unta wudhu jadi batal? Bukankah daging unta itu halal?
Sebagian ada yang mencari-cari hikmah di balik pernyataan Rasulullah SAW yang dicantumkan dalam Shahih Muslim di atas. Ada yang bilang karena unta itu dari setan, ada yang bilang karena unta itu dagingnya panas, ada yang bilang makan unta bikin sombong.
Syaikh Utsaimin, tokoh Wahabi, pernah mengatakan bahwa itu semua rekaan saja. Tidak penting untuk tahu apa hikmahnya, pokoknya kata nabi seperti itu, ya dilakukan saja.
Ulama yang mengatakan tidak batal wudhu karena makan unta punya kisah menarik. Sebenarnya konteks dalam Hadis Muslim di atas seperti ini:
Suatu saat setelah menghadiri jamuan makan malam dengan suguhan daging unta, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat hendak melaksanakan shalat. Saat itu terciumlah bau kentut. Nabi menunggu siapa sahabat yang akan mengulang wudhunya, tapi tidak ada yang keluar dari barisan jamaah shalat. Mungkin karena malu. Lantas untuk menutupi aib orang itu, Nabi lalu mengatakan, “Siapa yang tadi makan daging unta? Ayo kita wudhu lagi semua ya....” Demikianlah ketinggian akhlak Nabi Muhammad SAW yang tidak mau membuka aib orang lain. Silakan dibandingkan dengan bagaimana perilaku kita sekarang? []
Catatan: Tulisan ini telah terbit pada tanggal 08 Juli 2018. Tim Redaksi mengunggah ulang dengan melakukan penyuntingan dan penyelarasan bahasa.
___________
Penulis: Prof. Nadirsyah Hosen
Editor: Hakim
Kunjungi Juga
- Pasarkan Produk Anda dengan Membuka Toko di Marketplace Laduni.ID
- Profil Pesantren Terlengkap
- Cari Info Sekolah Islam?
- Mau Berdonasi ke Lembaga Non Formal?
- Siap Berangkat Ziarah? Simak Kumpulan Info Lokasi Ziarah ini
- Mencari Profil Ulama Panutan Anda?
- Kumpulan Tuntunan Ibadah Terlengkap
- Simak Artikel Keagamaan dan Artikel Umum Lainnya
- Ingin Mempelajari Nahdlatul Ulama? Silakan
- Pahami Islam Nusantara
- Kisah-kisah Hikmah Terbaik
- Lebih Bersemangat dengan Membaca Artikel Motivasi
- Simak Konsultasi Psikologi dan Keluarga
- Simak Kabar Santri Goes to Papua









_Jember.jpg)




Memuat Komentar ...