Hukum Menikahi Perempuan yang Ditinggal Suaminya

Laduni.ID, Jakarta - Pernikahan merupakan hal yang sangat sakral terutama dalam agama Islam, sehingga hukum tentang aturan pernikahan terbilang cukup kompleks dan rinci. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan madharat yang akan terjadi. Karena pernikahan akan berhubungan dengan status halal atau tidaknya satu pasangan, status anak, warisan, dan lainnya.
Dalam sebuah pernikahan ada beberapa kasus yang terjadi seperti seorang suami yang pergi meninggalkan istrinya dalam waktu yang cukup lama, atau hilang dikarenakan terjadi bencana alam yang keberadaan suaminya tidak diketahui, apakah masih hidup atau tidak dan tidak ada kepastian waktu kapan kembalinya. Suami yang pergi hingga tidak diketahui keberadaannya dalam waktu yang cukup lama dalam fiqih dikenal dengan istilah mafqud.
Dalam kondisi seperti itu ketidakjelasan tersebut menimbulkan masalah dalam rumah tangga, khususnya istri yang perlu mendapat kepastian untuk menikah dengan laki-laki lain. Jika kondisinya seperti di atas lalu sang istri menikah kembali dengan laki-laki lain, bagaimana hukumnya?
UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN
Support kami dengan berbelanja di sini:
.png)

 Rp157.000
Rp157.000
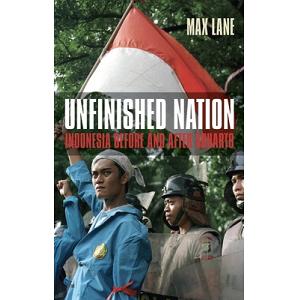 Rp602.000
Rp602.000
 Rp299.000
Rp299.000
 Rp0
Rp0












Memuat Komentar ...