Pantangan Menikah di Bulan Suro, Bukan Syariat tapi Adab Orang Jawa

Laduni.ID, Jakarta - Bagi masyarakat Jawa, Bulan Muharram atau Bulan Suro adalah salah satu bulan sakral setelah bulan puasa, Ramadhan. Bedanya, kalau bulan puasa penuh dengan ritual ibadah, baik pribadi maupun yang bersifat syiar agama, sedangkan Bulan Suro lebih banyak tidak menggelar acara kegembiraan. Terutama acara pernikahan dan khitan.
Sikap ini bukan tanpa sebab. Bagi penduduk Jawa, Suro merupakan bulan dukacita mendalam. Yakni terjadinya pembantaian keturunan Kanjeng Nabi SAW secara brutal. Hanya menyisakan balita bernama Sayyid Ali Zainal Abidin.
Karena itulah, dianggap sangat tidak etis menggelar acara yang intinya merayakan kebahagiaan di saat momen Bulan Suro. Sebagai tanda penghormatan kepada Kanjeng Nabi dan seluruh keturunannya, sebagian masyarakat Jawa sangat menjaga tradisi ini.
Mayoritas masyarakat Islam di Nusantara adalah penganut setia faham Ahlussunnah wal Jama’ah, dengan berpijak pada guru tasawuf seperti Imam Hasan Al-Bashri, Imam Al-Ghozali dan Imam Al-Junaid. Sehingga dirasa cukup memperingati Bulan Suro dengan cara demikian. Tidak ada yang perlu dianggap janggal.
Tentu berbeda dengan penduduk Persia. Mereka memiliki kedekatan psikologis yang luar biasa dari sisi historis. Bermula dari penaklukan Kemaharajaan Persia oleh Kholifah Amirul Mukminin Sayyidina Umar r.a. Konon, pasca penaklukan, Sayyidina Ali Karromallahu Wajhah menuju ke Persia.
Raja Persia jatuh hati dengan kealiman dan kelembutan Sayyidina Ali. Akhirnya secara sukarela masuk Islam. Dan ternyata diikuti oleh seluruh penduduk negeri tersebut.
UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN
Support kami dengan berbelanja di sini:

 Rp243.460
Rp243.460
 Rp898.000
Rp898.000
 Rp78.998
Rp78.998
 Rp444.000
Rp444.000


.jpg)









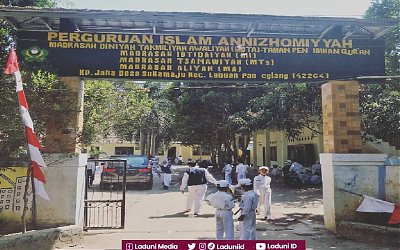

Memuat Komentar ...